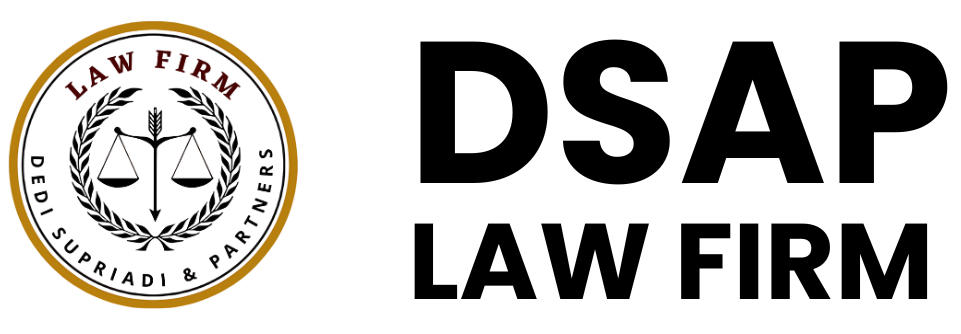Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang didirikan sejak tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 74/2020) memiliki fungsi untuk mengelola investasi pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Menurut situs resmi milik LPI, LPI dikatakan sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang tujuannya untuk membangun kesejahteraan bagi generasi mendatang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (ina.go.id). Dibalik tujuannya itu, LPI diharapkan dapat menjadi sarana penghubung untuk menarik investor asing agar berinvestasi di Indonesia. LPI dicanangkan sebagai mitra strategis investor asing maupun lokal dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek yang telah dijalankan adalah kerja sama dengan perusahaan asing yaitu Dubai Port World (DP World) yang merupakan raksasa operator terminal pelabuhan di dunia. Kerja sama tersebut melahirkan sebuah konsorsium yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendirian perusahaan patungan bernama PT INA DPWorld Investment (INA DPWorld). INA DPWorld kemudian bekerja sama dengan salah satu BUMN di bidang logistik untuk melakukan pengelolaan dan pengoperasian Belawan New Container Terminal di Selat Malaka (ina.go.id).
LPI tidak memberikan layanan investasi kepada publik melainkan hanya melaksanakan investasi pemerintah pusat yang pada dasarnya merupakan sebagian kewenangan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Menurut Pasal 154 ayat (3) UU Cipta Kerja investasi pemerintah pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan LPI sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 74/2020, Investasi pemerintah pusat sendiri diartikan sebagai pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya.
LPI didirikan dalam bentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi (PP 73/2020) Negara memberikan modal awal kepada LPI berupa dana tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). Modal awal tersebut hanya 20% dari total modal yang ditetapkan pemerintah kepada LPI berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP 74/2020 yang berjumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun rupiah). Satu tahun setelahnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi (PP 110/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi (PP 111/2021) negara baru “melunasi” keseluruhan modal sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan berdasarkan PP 74/2020. Melalui 3 (tiga) produk hukum tersebut dapat diketahui bahwa semua modal yang saat ini diberikan oleh negara kepada LPI dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara (PMN). PMN tersebut ada yang berbentuk cash dari APBN dan ada juga yang berasal dari pengalihan sebagian saham Seri B milik negara pada BUMN.
Saat ini asset under management LPI sudah menyentuh kisaran angka Rp163.417.975.000.000,00 (seratus enam puluh tiga triliun empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (ina.go.id). Artinya, ada pertumbuhan aset yang dikelola oleh LPI mulai saat pendiriannya hingga hari ini. Pertumbuhan aset tersebut tentunya bukan karena negara menyuntikkan dana terus menerus, melainkan atas hasil kerja nyata dari LPI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP tentang LPI yang menyebutkan bahwa aset LPI dapat berasal dari pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI di samping modal yang didapat dari penyertaan modal negara, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan/atau sumber lain yang sah.
Sebagai badan hukum atau entitas yang melaksanakan investasi tentunya LPI harus bisa meningkatkan nilai aset yang dikelolanya. LPI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai asetnya. Pihak ketiga dalam hal ini meliputi mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti DP World yang telah disebutkan sebelumnya (Peraturan Pemerintah tentang LPI). Ini artinya, walaupun LPI didirikan dan dimiliki oleh negara ia tidak melakukan pelayanan publik. LPI bisa dikatakan sebagai entitas investasi yang melakukan kegiatan dalam lapangan hukum perdata.
LPI sebagai entitas privat yang melakukan hubungan hukum keperdataan diberikan keistimewaan oleh negara agar asetnya tidak dapat disita kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. Pasal 160 ayat (3) UU Kerja menyebutkan “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Lembaga, kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman.” Ketentuan tersebut tidak hanya menabrak norma hukum lain tetapi juga tidak sesuai dengan teori hingga asas dalam hukum perdata.
Pertama, dalam tataran dogmatik hukum, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda sebagai aturan yang mengatur tentang hukum perdata materiil di Indonesia. Sama halnya dengan hukum materiil tersebut, HIR dan Rbg sebagai hukum formil warisan Belanda pun masih berlaku di Indonesia.
Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan pada intinya bahwa segala kebendaan milik debitur adalah jaminan bagi setiap perikatannya. Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 Rbg kemudian mengatur ketentuan tentang sita jaminan. Ketentuan mengenai sita jaminan tersebut merupakan wujud formil dari penerapan pasal 1131 KUH Perdata (Hukumonline, 2024). Adanya norma larangan penyitaan aset LPI tentunya akan berbenturan dengan Pasal 1131 KUHPerdata karena tidak semua kebendaan milik LPI menjadi jaminan atas perikatannya, melainkan hanya aset-aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. Maka dalam hal ini pula, tidak semua aset LPI dapat dimohonkan sita jaminan, melainkan hanya aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. Lantas bagaimana nasib mitra investasi LPI yang perikatannya tidak diberikan jaminan kebendaan jika suatu saat terjadi sengketa?
Persoalan ini kemudian memicu pertanyaan lanjutan, bagaimana jika LPI dipailitkan? Bukankah dalam hukum kepailitan dikenal adanya sita umum yang artinya seluruh harta kekayaan debitur pailit harus disita? Permasalahan ini sudah menjadi perhatian salah satu mahasiswa dari Universitas Airlangga dalam tesisnya yang berjudul “Sita Umum Kepailitan terhadap Lembaga Pengelola Investasi”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sita umum kepailitan hanya berlaku untuk aset yang dijaminkan sehingga mengakibatkan pelunasan utang kepada kreditor separatis dan preferen lebih terjamin daripada kreditor konkuren (Al Farizy, 2025).
Menurut pendapat penulis pribadi, ada kemungkinan kreditor separatis tidak mendapatkan pelunasan utang secara penuh dari aset yang telah dijaminkan LPI kepada kreditur tersebut, karena LPI harus terlebih dahulu membayarkan upah pegawai (pekerja) dan tagihan pajak yang tertunggak sebelum membayarkan utang kepada kreditur separatis. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Perpajakan) menyebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: a) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b) biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan c) biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Pasal 81 angka 36 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan dengan tegas bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
Kedua, secara teoretis larangan penyitaan aset secara mutlak berlaku hanya bagi aset negara. Yahya Harahap mengatakan “berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara atau daerah maupun terhadap uang dan barang yang dikuasai negara atau daerah” (Harahap, 2019: 381). Pengaturan tentang larangan penyitaan aset negara dituangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pertanyaannya sekarang, apakah aset LPI merupakan aset negara?
Ali Rido mengatakan bahwa suatu badan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu, a) memiliki harta kekayaan yang terpisah; b) mempunyai tujuan tertentu; c) mempunyai kepentingan sendiri; dan d) adanya organisasi yang teratur (Rido, 1986: 11). Sejalan dengan hal tersebut Arifin P. Soeria Atmadja menerangkan bahwa harta kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subjek hukum lain merupakan unsur paling pokok dari badan hukum. Harta kekayaan LPI sebagai badan hukum seharusnya terpisah dari kekayaan negara (Atmadja, 2009: 124). Kendati pun negara melakukan penyertaan modal negara, modal yang berasal dari kekayaan negara tersebut bertransformasi menjadi kekayaan badan hukum LPI. Hal ini sesuai dengan pendapat Dian Puji Simatupang yang mengatakan transformasi hukum uang publik menjadi uang privat terjadi ketika negara mendirikan suatu entitas bisnis berbadan hukum (Simatupang, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka secara teori, aset LPI adalah aset milik badan hukum LPI sehingga bukan lagi aset milik negara. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang LPI yang menyatakan “Aset LPI merupakan milik dan tanggung jawab LPI.” Konsekuensi hukum dari status aset LPI sebagai harta kekayaan badan hukum mengakibatkan aset LPI dapat menjadi objek tuntutan/sita, sehingga larangan penyitaan aset LPI tidak memiliki landasan secara teori.
Ketiga, dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kesetaraan/keseimbangan. Asas keseimbangan menghendaki bahwa hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perjanjian dalam proporsi yang seimbang (Cahyaningrum, 2024: 28). Menurut Nieuwenhuis, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin “…kontrak harus ‘ditolak’ jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat, karena dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan kontrak. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam kontrak bertimbal balik ialah ketidakseimbangan…” (Syaifuddin, 2012: 98). Norma larangan penyitaan aset LPI akan memberikan kedudukan menjadi LPI lebih tinggi dari mitra investasinya, dalam hal ini LPI memiliki hak yang lebih tinggi agar asetnya tidak dapat disita kecuali aset yang dijadikan jaminan. Berdasarkan hal tersebut maka norma larangan penyitaan aset LPI tidak sesuai dengan asas kesetaraan/keseimbangan dalam hukum perjanjian. Kedepannya, penulis menyarankan agar ada kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan eksistensi norma larangan penyitaan aset LPI serta kesesuaiannya dengan norma, teori, dan asas hukum perdata.
Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1024